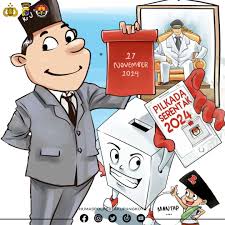Pendahuluan
Kerapuhan etika pemerintahan di Indonesia semakin menjadi sorotan tajam, terutama menjelang Pemilu 2024. Masyarakat, akademisi, dan pengamat politik bersamaan merasakan kegelisahan yang mendalam terhadap situasi ini, di mana kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin terkikis. Etika pemerintahan diharapkan berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara. Namun, dalam praktiknya, banyak penyelenggara negara yang terjebak dalam lingkaran kepentingan pribadi dan politik, mengesampingkan tanggung jawab mereka terhadap rakyat.
Fenomena korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang telah menjadi hal yang umum dan menyebar di berbagai tingkat pemerintahan, tak hanya merusak integritas individu penyelenggara, tetapi juga mengakibatkan dampak sistemik bagi masyarakat luas. Keterpurukan etika ini menciptakan gelombang kebangkitan suara penolakan di kalangan masyarakat, yang semakin cerdas dan kritis, terutama dengan meningkatnya akses terhadap informasi melalui media sosial dan platform digital. Dalam konteks pemilihan umum yang akan datang, tantangan ini menjadi semakin mendesak, di mana rakyat harus mampu memilih calon pemimpin yang tidak hanya memiliki visi dan misi yang jelas, tetapi juga integritas moral yang tinggi.
Lebih dari sekadar rancangan hukum dan regulasi yang ada, kerapuhan etika juga mencerminkan lemahnya sistem pendidikan dalam menginternalisasi nilai-nilai etika kepada generasi muda. Dalam keadaan di mana elit politik gagal menjadi teladan, masyarakat harus lebih proaktif untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari para pemimpin mereka. Pada akhirnya, untuk mengembalikan kepercayaan dan membangun iklim pemerintahan yang sehat, seluruh komponen bangsa perlu bersinergi dalam upaya memperkuat etika dan moralitas di ruang publik, sebelum suara rakyat ditentukan kembali dalam pemilihan yang penuh harapan tersebut.
Searah dengan kondisi tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah mendasar yang menyumbang kepada kerapuhan etika pemerintahan di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki keadaan ini dengan menekankan perlunya keteladanan dari elit politik.
Kerapuhan Etika dalam Aturan Formal
Salah satu faktor utama dari kerapuhan etika pemerintahan di Indonesia terletak pada ketidakmampuan aturan formal, seperti hukum, undang-undang, kode etik, dan kode perilaku, untuk mengubah dan membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Meskipun kerangka peraturan yang ada diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dalam pengelolaan negara, pada kenyataannya, implementasi dan pengawasan terhadap aturan-aturan tersebut sering kali tidak maksimal. Ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan individu terhadap etika publik dan norma-norma yang telah ditetapkan.
Sejak lama, pemikiran John Locke tentang kontrak sosial menekankan pentingnya keadilan dan moralitas sebagai dua pilar fundamental dalam membangun masyarakat yang beradab. Menurut Locke dalam karyanya yang berjudul “Two Treatises of Government” (1689), masyarakat yang ideal harus berlandaskan pada keseimbangan antara hak-hak individu dan tanggung jawab sosial. Keadilan, dalam perspektif Locke, tidak hanya mengacu pada penegakan hukum, tetapi juga pada sabda moral yang seharusnya mengarahkan perilaku individu dalam berinteraksi dengan sesama. Namun, nilai-nilai tersebut sulit terinternalisasi dalam kebijakan publik di Indonesia, di mana sering kali hukum dianggap sebagai sekadar formalitas yang harus dipatuhi, tanpa adanya kesadaran mendalam akan makna di baliknya.
Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa peraturan yang ada sering kali tidak diikuti, bahkan bisa menjadi alat legitimasi bagi praktik-praktik yang tidak etis. Misalnya, dalam kasus korupsi dan nepotisme yang terus merajalela, banyak individu menggunakan celah dalam hukum untuk membenarkan tindakan mereka, tanpa merasa terikat pada prinsip moral yang seharusnya mendasari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan formal telah dirumuskan dengan baik, tanpa adanya kesadaran dan komitmen pribadi untuk mematuhi etika, mereka akan gagal dalam menciptakan perubahan positif.
Salah satu contoh konkret dari lemahnya penerapan peraturan adalah dalam konteks pemilihan umum. Pada berbagai pemilu sebelumnya, bahkan dengan adanya undang-undang yang mengatur dana kampanye dan pengawasan, praktik penyalahgunaan wewenang dan penyuapan tetap terjadi. Para calon legislatif sering kali menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan struktur hukum yang ada untuk membenarkan tindakan yang sesungguhnya melawan etika. Di sini, terlihat jelas bahwa hukum tidak hanya gagal untuk menegakkan keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk melanggengkan perilaku tidak etis.
Lebih jauh lagi, kerapuhan etika dalam pemerintahan juga mencerminkan kesenjangan antara norma-norma yang tertulis dan perilaku yang dilakukan oleh individu dalam sistem. Kode etik yang seharusnya menjadi pedoman bagi penyelenggara negara sering kali hanya menjadi formalitas belaka, terabaikan dalam praktik sehari-hari. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, norma-norma tersebut tidak akan memiliki dampak yang signifikan.
Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat untuk menuntut adanya perubahan yang lebih substansial, tidak hanya sebatas pada perbaikan hukum tetapi juga pada penguatan kesadaran etika di kalangan individu. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaksanaan hukum perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan etika. Hanya dengan demikian, kerapuhan etika dalam pemerintahan dapat diminimalisir, dan keadilan serta moralitas sebagai pilar masyarakat yang beradab dapat diwujudkan.
Sistem pendidikan di Indonesia memainkan peran krusial dalam pembentukan karakter dan etika individu. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai etika sejak dini. Peneliti menyoroti bahwa kurikulum pendidikan saat ini masih kurang berorientasi pada pengembangan karakter dan etika sosial, dengan lebih banyak menekankan pada aspek kognitif dan akademis (Suhartini et al., 2021). Ketidakmampuan ini menimbulkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar pencapaian akademik; ia juga mempengaruhi cara individu berinteraksi di masyarakat dan memahami tanggung jawab sebagai warga negara.
Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam masyarakat, menciptakan tantangan baru dalam proses pendidikan. Meskipun dunia pendidikan seharusnya beradaptasi dengan kebutuhan zaman, nilai-nilai moral dan etika sering kali terabaikan dalam pengajaran sehari-hari. Kurikulum yang berfokus pada ujian dan pencapaian akademik menempatkan etika sebagai hal yang sekunder, jika tidak disebut sebagai sesuatu yang hampir tidak tampak dalam mata pelajaran yang diajarkan. Sementara itu, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati yang seharusnya ditanamkan sejak dini mengalami pengabaian.
Tanpa adanya kesadaran etika yang tinggi dalam diri individu, aturan formal dan regulasi yang ada dalam masyarakat tidak akan berfungsi secara optimal. Individu yang tidak memiliki basis etika yang kuat cenderung tidak mematuhi hukum dan kebijakan yang ada, berpotensi menciptakan situasi di mana praktik-praktik tidak etis menjadi kebiasaan. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, penyelenggara negara yang tidak memiliki kesadaran etika akan lebih mudah terlibat dalam tindakan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang, yang pada gilirannya melanggengkan budaya ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Disamping itu, keterpurukan dalam sistem pendidikan etika juga menciptakan ketidakpahaman di kalangan generasi muda tentang tanggung jawab sosial mereka. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, mereka cenderung apatis terhadap isu-isu publik dan tidak berpartisipasi dalam upaya kolektif untuk menciptakan perubahan. Sikap tidak peduli ini dapat menjadi bibit budaya korupsi yang lebih besar di masa depan, karena generasi yang tidak terbiasa dengan nilai-nilai etika akan menganggap pelanggaran sebagai hal yang biasa.
Selanjutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat di mana nilai-nilai etika dapat diterapkan dan diperkuat melalui pengalaman langsung, baik dalam interaksi antar siswa maupun dalam hubungan antara siswa dan guru. Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum, sekolah dapat memperkenalkan siswa pada konsep keadilan, empati, dan kerjasama, yang semuanya merupakan bidang penting dalam pengembangan individu yang etis. Namun, saat ini, banyak sekolah yang belum melaksanakan ini secara konsisten dan efektif, sehingga siswa tetap terputus dari pengalaman pendidikan yang sesungguhnya.
Reformasi dalam sistem pendidikan diperlukan untuk mengubah lanskap ini. Penekanan pada pengembangan karakter dan etika sosial dalam kurikulum harus menjadi prioritas, diiringi dengan pelatihan untuk para pendidik agar mereka dapat mendidik siswa tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal moral. Penguatan pendidikan karakter diharapkan dapat membangun kesadaran etika yang lebih kuat dan mengurangi kerapuhan etika dalam masyarakat.
Dengan kesadaran etika yang ditanamkan sejak dini, individu akan lebih mampu menghargai dan mematuhi aturan formal yang ada, menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan individu yang pintar, tetapi juga individu yang etis, yang siap menjalani tanggung jawab sosialnya dalam membangun bangsa.
Esensi Berkuasa: Dewan Etika atau Kepentingan Pribadi?
Dalam banyak kasus, esensi berkuasa di kalangan elit politik di Indonesia semakin kehilangan arah. Seharusnya, kekuasaan yang diemban oleh para politisi bertujuan untuk melayani masyarakat dan mendorong kesejahteraan rakyat. Namun, realitas yang ada justru menunjukkan bahwa beberapa elit politik cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri di atas kepentingan publik. Hal ini tercermin dari praktik korupsi, nepotisme, dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang terus berlangsung meskipun banyaknya regulasi yang disusun untuk menanggulanginya.
Praktik korupsi yang merajalela telah menjadikan etika dan moralitas publik sering kali terabaikan. Menurut Suharto (2019), budaya patronase dan klienelisme di kalangan elit politik menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana kepentingan politik pribadi lebih diutamakan dibandingkan dengan komitmen terhadap etika publik. Politisi, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, justru bertransformasi menjadi penguasa yang mencari keuntungan pribadi. Hal ini bukan hanya merugikan integritas individu-individu dalam pemerintahan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya mereka percayai.
Ketidakpuasan publik terhadap pengelolaan pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh elit politik menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Data sensus sosial mencerminkan penurunan kepercayaan publik yang drastis, terutama saat negara dihadapkan pada skandal-skandal korupsi yang terungkap ke permukaan (Bps.go.id, 2023). Ketidakpuasan ini bukan tanpa alasan, sebab masyarakat sering kali dihadapkan pada kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik dan pelayanan publik yang tidak memadai.
Kondisi ini menciptakan spiral negatif, di mana rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membuat mereka cenderung apatis dan skeptis terhadap setiap inisiatif yang diambil oleh pemerintah. Akibatnya, program-program yang seharusnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan publik sering kali menemui jalan buntu, karena masyarakat merasa bahwa elit politik tidak memiliki niat baik untuk melayani mereka. Dalam masyarakat yang tidak mempercayai penguasa, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat sulit, sehingga mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Lebih jauh lagi, tindakan penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan citra pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ketika dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disalahgunakan atau dikorupsi, maka masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak efektif. Kurangnya investasi dalam sektor-sektor penting tersebut menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyat, memperburuk kualitas hidup bagi banyak orang.
Dalam konteks ini, menjadi sangat penting bagi elit politik untuk kembali kepada esensi asli kekuasaan mereka, yaitu melayani masyarakat. Mereka harus introspeksi dan berkomitmen untuk membangun budaya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi dalam sistem yang ada, diiringi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, adalah langkah-langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Hanya dengan komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam pemerintahan, masyarakat Indonesia dapat berharap pada terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, di mana keadilan dan kesejahteraan bagi semua dapat menjadi bagian integral dari proses pembangunan bangsa. Kepercayaan dan dukungan dari masyarakat adalah kunci dalam menciptakan perubahan positif, dan ini hanya dapat dicapai jika para pemimpin berani menegakkan integritas dan bertindak untuk kepentingan rakyat.
Kesalahan dalam Sistem Pendidikan dan Internalitas Etika
Kerapuhan etika dalam masyarakat juga disebabkan oleh kesalahan sistem pendidikan yang belum berhasil mendukung internalisasi nilai-nilai etika. Untuk menciptakan masyarakat yang etis, sistem pendidikan harus menekankan pentingnya karakter dan moralitas. Menurut Dewey (1916), pendidikan seharusnya mampu menjalin hubungan antara individu dengan masyarakat, dan mengajarkan nilai-nilai etika yang relevan.
Dengan tidak terinternalisasinya etika dalam konteks sistem pendidikan, generasi muda dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup dengan kurangnya pemahaman akan norma-norma etika yang penting. Akibatnya, mereka akan berpotensi menjadi penyelenggara negara yang tidak peka terhadap etika ketika mereka terjun ke dunia politik.
Memperbaiki Kerapuhan Etika Pemerintahan
Menanggapi persoalan kerapuhan etika di Indonesia tersebut, akuntabilitas dan reformasi menjadi hal yang membutuhkan perhatian serius. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:
Pertama, Revisi Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu : Reformasi sistem pendanaan politik sangat penting agar lebih transparan dan akuntabel. Melibatkan akuntan publik independen dalam proses audit dan verifikasi dapat memperkuat integritas dalam pendanaan politik (Fauzan, 2020).
Kedua, Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-nilai Pancasila : Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pemerintah. Penerapan nilai luhur Pancasila dalam regulasi dapat memberikan bimbingan etika yang kuat kepada penyelenggara negara.
Ketiga, Menjadikan Etika sebagai Tolok Ukur : Untuk menjawab harapan publik terhadap keadilan dan kesejahteraan, penting untuk menjadikan etika sebagai tolok ukur penilaian integritas para penyelenggara negara. Pembentukan lembaga pengawas independen yang fokus terhadap penegakan norma-norma etika juga perlu dipertimbangkan (Widodo, 2022).
Keempat, Membudayakan Keteladanan di Kalangan Penyelenggara Negara : Politisi yang berbudi pekerti dan beretika seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Dengan menciptakan citra positif, mereka tidak hanya akan menginspirasi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi praktik penyalahgunaan wewenang.
Kesimpulan
Kerapuhan etika pemerintahan di Indonesia menjelang Pemilu 2024 adalah tantangan serius yang berbasis pada kesadaran individu dan integritas institusi. Upaya mereformasi pemerintahan dan mendidik masyarakat akan memakan waktu, tetapi sangat diperlukan untuk menciptakan budaya pemerintahan yang beretika. Tanpa adanya keteladanan dari elit politik, maka harapan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan akan tetap menjadi impian semata. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk menciptakan negara yang tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga pada etika dan moralitas yang tinggi.
Daftar Pustaka
- Dewey, J. (1916). Democracy and Education . New York: Macmillan.
- Fauzan, K. (2020). “Reformasi Pendanaan Partai Politik di Indonesia.” Jurnal Kebijakan Publik , 5(1), 43-58.
- Locke, J. (1689). Two Treatises of Government . London: Awnsham Churchill.
- Suhartini, N. et al. (2021). “Pendidikan Karakter dalam Sistem Pendidikan Nasional: Evaluasi dan Rekomendasi.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , 6(2), 89-104.
- Suharto. (2019). “Politik Patronase dan Korupsi di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis.” Jurnal Ilmu Sosial , 10(2), 210-224.
- Widodo, G. (2022). “Pengawasan Etika dalam Pemerintahan: Menjawab Tantangan Keterbukaan dan Akuntabilitas.” Jurnal Hukum dan Etika , 3(1), 15-30.